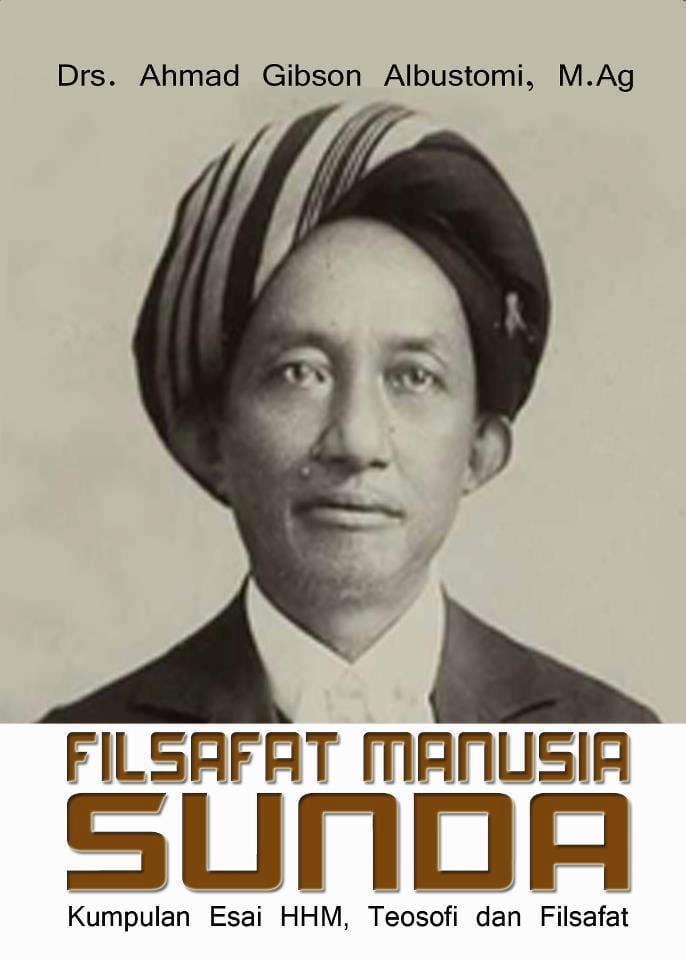Diakui atau tidak, keberadaan Ki Sunda (bahasa, aksara, sastra, agama) tinggal menanti sang penjemput ajal tiba. Ibarat pepatah, hidup enggan mati tak mau.
Pasalnya, kehadiran mojang-jajaka selaku generasi penerus sekaligus penjaga khazanah kesundaan tak mau belajar kesundaan. Sekadar contoh, kawula muda bangga berkomunikasi dengan memakai bahasa persatuan (Indonesia ala Betawi) di Tanah Pasundan.
Ini yang dikeluhkan oleh Ahmad Gibson Albustomi, dosen Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam bukunya, Filsafat Manusia Sunda: Kumpulan Esai HHM, Teosofi dan Filsafat (November, 2012) dengan mengajukan pertanyaan melalui tulisan; “Basa Indung” dan “Basa Lulugu” dalam Kurikulum Lokal Bahasa Indonesia (Fragmen 16); Kuring Urang Sunda (?) (Fragmen 16).
Merenungkan Basa Sunda
Saat membaca tulisan tentang “Basa Indung” dan “Basa Lulugu” dalam Kurikulum Lokal Bahasa Indonesia, Baba Icon sapaan akrabnya menuliskan, Basa Indung orang Sunda adalah bahasa Sunda, hal ini tidak lagi perlu diperdebatkan.
Akan tetapi bahasa Sunda yang mana? Apakah bahasa Sunda yang dikenal dan dipakai oleh masyarakat Sunda Priangan? (Bandung, Cianjur, Sumedang, Garut, Tasikmalaya dan Ciamis), ataukah basa Sunda non-Priangan lainnya seperti bahasa Sunda dengan dialek yang digunakan oleh masyarakat di wilayah seperti Cirebob, Banten, Bogor dan wilayah Sunda lainnya? (h. 113).
Pada tulisan Kuring Urang Sunda (?) menerangkan, lahir dari Rahim keluarga Sunda pituin, sejak kecil hidup dalam lingkungan masyarakat Sunda. Karena biasa, maka tidak ada hal yang menarik untuk diperhatikan berkenaan dengan ke-Sunda-anku.
Setelah sadar bahwa selama ini atmosfer budaya asing lebih dominan membentuk perilaku dan konstruk nilai budaya yang hidup dalam pikiran dan pengalaman batin, aku bertanya-tanya, siapa aku? Betulkah saya orang Sunda?
Ngan nangtayungkeun pikukuh,
Mun enya tariking angina,
Kodrat irodat pangeran,
Nu mindahkeun birit aing,
Lahaola wala kuwata,
Aing nu hajating aing.
Jangan-jangan “Kuring lain urang Sunda?” Apalagi ada yang menyebut bahwa orang Sunda harus malu bila tidak bisa main kecapi, suling, serta alat-alat musik Sunda lainnya. Atau, berbahasa Sunda dengan baik (ala Mataram).
Aku memang merasa malu, tak ada satu alat musik Sunda pun yang bisa kumainkan. Tak ada satu pun yang menjadi bagian dari kehidupanku. Sampai sekarang aku hanya menjadi penikmat seni musik, tapi tidak pernah memiliki kemampuan (kabisa) untuk memainkan alat-alat musik. (h. 193-194).
Sungguh perlu kita mengajukan pertanyaan menukik: Adakah manusia Sunda sejati itu?
Haji Hasan Mustapa (HHM) menguraikan, inti pemikiran HHM khususnya tentang manusia dan eksistensi manusia terangkum dalam dua naskah besarnya, yaitu Gelaran Sasaka di Kaislaman dan naskah (Ajip Rosidi menyebutnya sebagai catatan ringkas) Martabat tujuh.
Bila memakai perspektif filsafat eksistensialisme Gelaran Sasaka di Kaislaman merupakan naskah yang menjelaskan fase-fase aktualisasi eksistensi seorang manusia yang berhadapan dengan sejumlah norma-norma sosial yang oleh individual manusia pada umumnya disikapi (secara sadar) dan secara faktual (di luar kesadaran sadar) merupakan unsur yang mengancam eksistensi dan otonomi individu.
Dalam naskah tersebut HHM menegaskan bahawa justru tekanan-tekanan norma sosial (agama) tersebut secara eksistensial merupakan unsur dialektis yang menjadi potensi pendorong dan dinamisator bagi munculnya proses penyadaran eksistensi manusia.
Gelaran Sasaka di Kaislaman sebagai fase aktualisasi manusia diawali oleh fase (maqomat) Islam hingga Kurban. Maqomat Islam sebagai maqomat awal hingga maqomat sahadah, digambarkan HHM sebagai maqomat yang sarat dengan sikap “menyebelah’ dari individu manusia dalam memendang apa pun, baik dari maupun sesuatu diluar diri. Dan mulai maqomat sidiqiah hingga kurban sikap-sikap menyebelah tersebut secara bertahap hilang dari cara pandang individu manusia.
HHM melihat bahwa pada gelaran inilah sikap dan cara pandang keberagamaan manusia lahir dalam pengertian yang sesungguhnya.
Naskah Martabat ketujuh-Nya HHM menjelaskan fase lanjutan dari fase-fase yang dilalui dalam Gelaran Sasaka di Kaislaman. Suatu fase puncak dalam sikap dan cara pandang keagamaan yang berakhir pada maqomat Insan Kamil. Maqom yang tidak lagi melihat perbedaan dan pertentangan dalam kehidupan di dunia sebagai kenyataan hakikiah (h. 4-5).
Perbedaan-perbedaan dan pertentangan tersebut tidak lebih disebabkan oleh cara pandang manusia yang memiliki kecenderungan menyebelah, mengutub. Cara pandang yang terlahir dari sikap yang membedakan secaar radikal sifat-sifat jamal dan jalal Tuhan yang termanisfestasi dalam keragaman alam makhluknya. Individu manusia yang telah sampai pada maqom Insan Kamil, memendang bahwa keragaman tersebut tak lebih dari manifestasi dari sifat Jamal dan Jalal Tuhan yang merupakan direvarasi (tajalli) dari sifat kamal (kemahasempurnaan Tuhan) (h. 5-6).
Dalam naskah Bale Bandung, sebagai contoh, HHM mendeskrifsikan konsep pencapaian kesempurnaan manusia (Insan Kamil) yang disimbolkan dengan tokoh mitos Sunda Munding Laya di Kusumah, yang telah mampu membinasakan tujuh Guriang yang merupakan ilustrasi terlewatinya tujuh tingkatan (maqomat) dan mendapatkan Lalayang Domas. (h. 10)
Perjalanan kehidupan manusia digambarkan HHM secara sisitematis dalam naskah Gelaran Sasaka di Kaislaman. Nasakah tersebut merupakan naskah yang bersambung dalam alur, namun berbeda pada karakter serta penekanan personal yang diungkapkan (h. 18).
HHM menjelaskna bahwa orang yang memutuskan untuk memutus tali relasi dengan eksistensi lain dari pada mengalami kemajuan malah akan mengalami kemunduran dan terjerembab dalam kekufuran (penolakan yang terus menerus). Sementara orang yang membuka diri untuk relasi dengan eksistensi lain akan meningkat pada perwujudan eksistensi yang lebih tinggi. Orang harus mengakui keberadaan makhluk-makhluk yang tidak bisa disangkal eksistensinya (h. 27-28).
Proses membuka relasi dalam atmosfer partisipasi ini digambarkan HHM dalam dangdingnya:
Rempug semu jeung salembur,
Bear budi jeung pangampih,
Mustika tara kasangka,
Bisi batur pada manggih,
Diudag tata satata,
Ditungtik surtina buni.
HHM menjelaskan bahwa inti keputusan dari dilema dialektis eksistensial adalah persoalan relasi. Menutup diri atau membuka diri. HHM secara tegas menjelaskan bahwa kecenderungan orang untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dalam prinsip “kesenangan” secara membabibuta berkonsekuensi munculnya tuntutan untuk memutus tali relasi dengan eksistensi lainnya (h. 28-29).
Konsep eksistensi (jati diri) manusia diungkap HHM memang tidak secara spesifik ditujukan untuk merumuskan konsep jati diri manusia Sunda. Namun, karena sering dan biografi serta referensi horizon pembicaraan sangat kental kesundaannya.
Bagi HHM, eksistensi (jati diri) manusia, khususnya manusia Sunda, bukanlah sesuatu yang bersifat instan. Melainkan mengalami proses yang sangat panjang, dan ketika hadir di dunia pun, ia mengalami proses yang panjang pula. Manusia bukanlah “barang” jadi, melainkan “wujud” yang senantiasa berada dalam proses.
Sejarah primordial manusia berakar dari Tuhan, sebagai refresentasi paling sempurna dari kehadiran Tuhan pada makhluknya. Konsep dasar ini dalam dunia tawasuf dikenal dengan istilah tajali. Konsep yang menjelaskan bagaimana segala sesuatu, termasuk manusia ada dan mengada; munculnya realitas plural dari yang tunggal. Konsep yang selanjutnya melahirkan rumusan tentang Insan Kamil, manusia sempurna (h. 33).
Jejak Mahakarya
Rupanya buku Filsafat Manusia Sunda adalah kumpulan tulisan karya Ahmad Gibson Albustomi, yang berisi permenungan filosofis dan religious atas keberadaan manusia, terutama kaitannya dengan tatar Sunda. Tulisan-tulisan yang terhimpun dalam buku ini semula merupakan 30 artikel lepas yang tercecer dalam surat kabar dan majalah serta makalah untuk forum diskusi dan seminar.
Dari amatan selayang pandang Hawe Setiawan saat memberikan Kata Pengatar menguraikan atas gagasan dalam bunga rampai ini, terlihat adanya tiga kecenderungan tematis; Pertama, penafsiran Gibson atas perenungan tasawuf almarhum HHM (1852-1930), penghulu Islam di Aceh, kemudian di Bandung pada zaman kolonial serta penyair mistik Sunda terbesar.
Kedua, pemikiran Gibson mengenai masalah-masalah umum menyangkut hubungan antara Sunda sebagai lingkungan budaya dan Islam sebagai keyakinan religious yang biasanya terwakili oleh fase “Sunda-Islam” serta pemikirannya mengenai berbagai aspek dari sosok orang Sunda.
Ketiga, perenungan Gibson sebagai muslim atas sikap, pandangan dan perilaku keberagamaan di Indonesia. Meskipun, kecenderungan pertama dapat dapat dikatakan lebih menonjol daripada dua kecenderungan berikutnya. Jika pada kecenderungan pertama HHM dibaca sebagai pokok permenungan, maka pada dua kecenderungan berikutnya HHM seringkali disinggung-singgung sebagai salah satu bahan rujukan (h. viii).
Sehubungan dengan gayanya, tulisan-tulisan Gibson dalam buku ini dapat dibagi ke dalam dua kecenderungan; gaya impersonal di satu pihak dan gaya personal pihak lain. Tentu, sebagaimana lazimnya bunga rampai, nada yang diperdengarkan dan suasanayang dibangun oleh tulisan-tulisan dalam buku ini tidak seragam.
Sebagian besar tulisan Gibson dalam buku ini mengandalkan gaya impersonal yang mengajak pembaca untuk berdiskusi dalam suasana diskursif. Sebagian kecil tulisannya di sini mengandalkan gaya personal, bahkan dengan menekankan sudut pandang orang pertama, hingga mendekati semacam pernyataan diri, misalnya “Aku ingin jadi Mualaf” dan “Kuring Urang Sunda” ¾ dan justru kelompok tulisan inilah yang bagi saya sendiri lebih menarik ketimbang kelompok tulisannya yang disebutkan lebih dulu (h. ix).
Jika benar bahwa HHM merupakan representasi ideal budayawan dan pencetus konsep ideal manusia Sunda, maka untuk mengkaji persoalaan kesundaan, persiapan dan bekal yang harus dipersiapkan dan dimiliki kurang lebih sama. Oleh karena itu, keberadaan konsorsium sebagai alat dan sistem kajian untuk mengorek mutiara dari khazanah budaya Sunda yang dipendam dan terpendam menjadi prasyarat yang mutlak adanya (h. 6).
Kiranya, tembang Pop Sunda “Urang Sunda” harus kita teriakkan supaya orang Sunda bangun untuk berlomba-lomba mencari jati diri Ki Sunda.
Gancang geura hudang buka ceuli buka mata
Geura tembongkeun urang sunda oge bisa
Tembongkeun urang ge bisa mela nagara
Tembongkeun urang ge bisa jadi pamimpin
Urang ge bisa nangtung ajeg jeung kawasa
Lain saukur bisa unggut jeung kumawula.
Walhasil, jangan ngaku orang Sunda kalau belum membaca buku ini. Setuju? Selamat membaca!
Editor: Hafidz Azhar