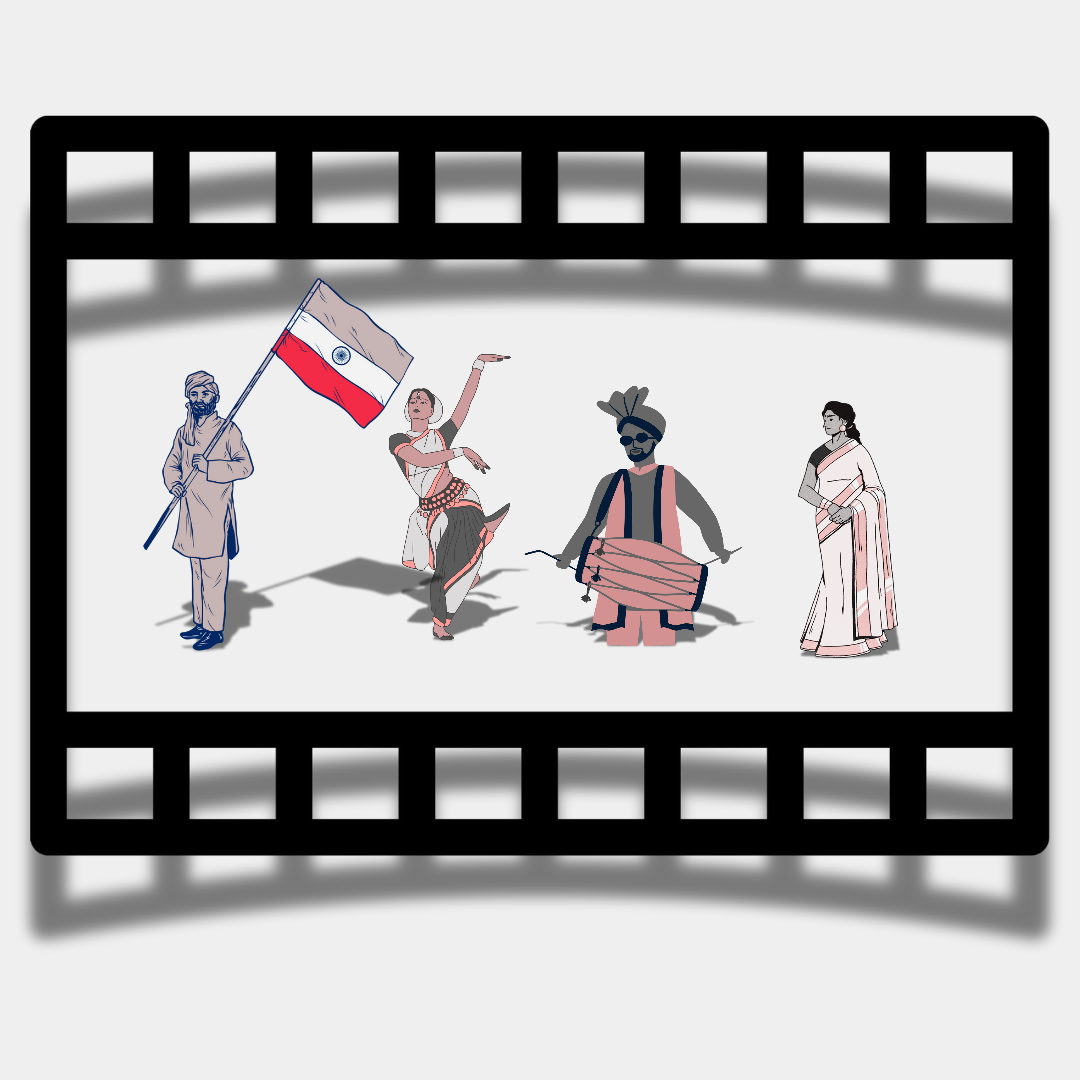Pada awal 1960-an, dengan semangat anti-Barat yang menggebu, Sukarno mencemooh musik pop Barat dengan sebutan “ngak-ngik-ngok”. Ia menganggap musik tersebut sebagai ancaman terhadap nilai-nilai ketimuran. Bahkan, Koes Plus—yang dijuluki The Beatles Indonesia—pernah dipenjara akibat kebijakan ini. Tak hanya industri musik, perfilman pun terkena dampaknya. Pada tahun 1964, Sukarno membentuk Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS) untuk membendung masuknya film Hollywood, menggantikannya dengan film-film dari Timur, termasuk dari India.
Namun, perubahan tak terhindarkan. Setelah Sukarno dilengserkan, Suharto dengan Orde Barunya kembali membuka pintu bagi film-film Barat, dan mendominasi bioskop Indonesia. Meski demikian, di tengah arus deras film Hollywood, film-film India justru tetap memiliki tempat istimewa di hati masyarakat. Mungkin karena jejak budaya India telah lama berakar di Nusantara—melalui proses akulturasi, asimilasi, dan sinkretisme yang berlangsung sejak abad pertama Masehi. Atau boleh jadi, karena melodrama, nilai kekeluargaan, serta emosinya begitu dekat, berbicara dalam bahasa yang tak butuh terjemahan: tentang cinta, keluarga, dan air mata yang abadi.
Pada dekade 1980-an hingga 1990-an, layar lebar nasional dipenuhi film-film Bollywood, menjadikannya lebih dari sekadar hiburan—ia melebur menjadi bagian dari konsumsi budaya yang lekat dalam kehidupan sehari-hari. Masa kecil saya sendiri tidak lepas dari warna-warni film India yang semarak. Saya masih ingat betul nama-nama yang selalu muncul di end credit: Sridevi, Mithun Chakraborty, Irrfan Khan, Naseeruddin Shah, Om Puri, Amitabh Bachchan, Aamir Khan, Kajol, Salman Khan, Shahrukh Khan, Johnny Lever, Akshay Kumar, Kareena Kapoor, Sanjay Dutt, Aishwarya Rai, Ajay Devgan, Anil Kapoor, Jackie Shroff, hingga Amrish Puri—alias Tuan Takur yang legendaris itu.
Film-film India menyusup ke keseharian, membentuk selera, dan melahirkan nostalgia yang bertahan hingga kini. Di Bandung, misalnya, ada ungkapan khas untuk mereka yang sering datang terlambat: “Euh, telat, jiga polisi India wae!” Ungkapan ini terdengar sepele, tetapi menyiratkan bagaimana Bollywood telah meresap ke dalam budaya tutur kita. Tak hanya itu, mereka yang wajahnya sedikit mirip orang India sering mendapat julukan spontan—uhuy: Vijay, Mitun, atau Takur. Sebuah pengakuan bahwa Bollywood bukan hanya milik layar lebar, tetapi juga hidup dalam obrolan sehari-hari, dalam melihat dan menamai dunia di sekitar kita.
Film-film India telah menanamkan jejaknya dalam berbagai aspek budaya populer Indonesia. Lagu-lagunya kerap bergema dalam hajatan, diaransemen ulang menjadi, misalnya, dangdut dan pop Sunda. Televisi nasional—yang saat itu masih menjadi jendela utama hiburan—menayangkannya berulang kali, seolah memastikan bahwa pesona Bollywood tak lekang oleh waktu. Film India bukan sekadar tamu yang singgah sesaat, tetapi pengaruh yang mengakar, memperkaya lanskap budaya pop Indonesia: dari selera musik hingga cara bercerita dalam film dan televisi.
Memasuki pertengahan 2000-an, popularitas film India mulai meredup. Mungkin karena formula Bollywood yang semakin membosankan. Di saat yang sama, industri film nasional mulai bergeliat, sementara Korea Selatan semakin agresif dengan invasi budayanya melalui musik dan film. Namun, ada faktor lain yang turut berperan: perubahan pola konsumsi media. Jika pada era 1990-an film India mudah diakses melalui televisi dan kaset VCD bajakan yang beredar luas, maka memasuki era 2000-an, internet dan platform digital mengubah cara masyarakat menikmati hiburan. Stasiun televisi nasional yang dulunya rutin menayangkan film-film Bollywood mulai beralih ke sinetron lokal dan program realitas yang lebih menarik perhatian pasar.
Dalam tulisan ini, saya tidak akan membahas film Korea. Fokus saya tetap pada film India—tetapi bukan yang Bollywood-sentris, dengan segala dramanya yang berlebihan, nyanyian, dan tarian yang seolah tak terpisahkan dari narasi. Kali ini, saya ingin mengangkat film-film India yang menurut saya benar-benar layak ditonton, terutama yang menawarkan pendekatan berbeda dari stereotip Bollywood yang selama ini mendominasi. Bagi saya, ada dua film India yang pantas dibahas lebih serius. Film-film ini memiliki kekuatan tersendiri—baik dari segi narasi, sinematografi, maupun gagasan yang diusung. Sisanya? Akan saya bahas sekilas saja—karena, seperti biasa, saya keburu sibuk dengan ini dan itu.
Haider (2014): Hamlet di Kashmir
Alejandro Jodorowsky pernah berkata:
“When you make a picture, you must not respect the novel. It’s like you get married, no? You go with the wife, white, the woman is white… You take the woman, if you respect the woman, you will never have a child. You need to open the costume and to… To rape the bride. And then you will have your picture. I was raping Frank Herbert, raping, like this! But with love, with love”.
Sebrutal dan seproblematis apa pun pernyataan di atas, ia mencerminkan bagaimana seorang sineas besar memperlakukan sumber adaptasi—tanpa rasa takut, bahkan cenderung destruktif. Adaptasi, menurut Linda Hutcheon (2006), bukan sekadar alih wahana, melainkan transformasi yang membangun keterlibatan intertekstual dengan teks asli. Ia dapat menjadi pemaknaan ulang yang mendekonstruksi narasi awal sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan politik yang baru.
Jika Jodorowsky pernah membayangkan dirinya “merusak” Dune, maka Vishal Bhardwaj melakukan hal serupa terhadap Hamlet, tetapi dengan sensitivitas lokal yang tajam dan penuh perhitungan. Sejak rilis pada Oktober 2014, Haider menjadi salah satu film paling kontroversial dalam sejarah perfilman India. Film ini bukan sekadar reimagination dari Hamlet, melainkan wacana sinematik yang menyoroti luka kolonial yang masih menganga dalam konflik Kashmir.
Dalam konteks ini, Haider tidak hanya berfungsi sebagai adaptasi sastra, tetapi juga sebagai kritik terhadap historiografi kekuasaan. Sebagaimana dinyatakan oleh Shohini Ghosh (2015), Haider menjadi alat perlawanan terhadap narasi negara yang sering kali mengaburkan represi di wilayah konflik. Reaksi keras dari pemerintah India pun tak terhindarkan. Tuduhan anti-nasionalis menyerang Bhardwaj, yang menanggapinya dengan santai:
“I’m also an Indian, I’m also a patriot, I also love my nation. So I won’t do anything which is anti-national. But what is anti-human? I will definitely comment on it”.
Pernyataan Bhardwaj di atas mengingatkan kita bahwa sinema, dalam kondisi tertentu, dapat bertindak sebagai wacana kontra-hegemonik. Edward Said dalam Culture and Imperialism menekankan bahwa narasi dominan selalu mengonstruksi sejarah dari perspektif kekuasaan, sementara karya-karya yang menentang dominasi ini berfungsi untuk membuka ruang kritik terhadap bentuk-bentuk penindasan yang dilegitimasi oleh negara.
Bayangkan Trilogi Insiden: Saksi Mata karya Seno Gumira Ajidarma diadaptasi menjadi film layar lebar dan diputar di seluruh bioskop Indonesia. Atau Zaman Edan, Kandang Hiu: Timor-Timur 1998-1999 karya Richard Lloyd Parry dijadikan dokumenter ala The Act of Killing dan The Look of Silence karya Joshua Oppenheimer. Konsekuensinya jelas: narasi resmi akan terguncang, batas antara ingatan nasional dan ingatan subaltern akan kembali dipertanyakan. Dalam konteks ini, Haider adalah sebuah film yang menolak tunduk pada eufemisme politik.
Dengan cerdas, Bhardwaj menerjemahkan kompleksitas Hamlet ke dalam narasi politik kekerasan di Kashmir. Shahid Kapoor sebagai Haider/Hamlet menampilkan kegilaan dan konflik batin dengan luar biasa, sementara Irrfan Khan sebagai Roohdaar (Ghost) benar-benar mencuri perhatian. Lebih jauh, performa Tabu sebagai Ghazala (Queen Gertrude dalam Hamlet) memberikan lapisan psikologis yang dalam, menambah kompleksitas dalam membaca trauma dan ambiguitas moral dalam film ini.
Film ini ditutup dengan tragedi yang tidak hanya menggambarkan nasib Haider, tetapi juga menjadi refleksi atas siklus perebutan kekuasaan yang tak pernah berakhir. Dalam pandangan Agamben, negara modern sering kali mempertahankan kekuasaannya melalui mekanisme state of exception, di mana hukum justru dilegitimasi untuk menindas. Haider mengingatkan kita bahwa manusia, kapan pun dan di mana pun, tidak pernah belajar dari sejarah kelam mereka sendiri.
Atau, dalam kata-kata Jodorowsky:
“Movies are an art. More than an industry. And it’s the search of the human soul: as painting, as literature, as poetry. Movies are that for me.”
PK (2014): Mengajarkan Kita Bertanya pada Sang Khalik
PK (2014) adalah film drama-komedi fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Rajkumar Hirani dengan Aamir Khan sebagai pemeran utama. Film ini mengusung konsep klasik tentang seorang outsider yang mengamati masyarakat dengan perspektif keheranan. Dalam narasi film, PK menceritakan kisah seorang alien yang terdampar di bumi setelah alat komunikasinya dicuri. Dalam pencariannya untuk kembali ke planet asalnya, ia justru tersesat dalam sistem sosial dan keagamaan manusia yang tampak penuh dengan absurditas dan kontradiksi. Perspektif outsider ini memiliki relevansi dengan teori sociology of knowledge yang dikembangkan oleh Peter Berger dalam The Sacred Canopy, yang menyatakan bahwa agama sering kali membentuk dan memantapkan struktur realitas sosial untuk mempertahankan status quo. Dalam hal ini, PK memperlihatkan bagaimana agama berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang kerap membingkai realitas dalam bentuk doktrin dan ritual yang tidak selalu rasional.
Sejak pertengahan film, gagasan yang diangkat oleh PK mengingatkan pada puisi Rumi yang mengekspresikan pencarian Tuhan di berbagai tempat ibadah, namun akhirnya menemukan-Nya dalam hati sendiri. Konsep ini sesuai dengan pemikiran dalam sufisme, di mana pengalaman spiritual personal lebih utama dibandingkan dengan struktur agama yang bersifat institusional. Dalam konteks film, PK menggambarkan pencarian spiritual yang serupa—bukan dengan menyangkal keberadaan Tuhan, tetapi dengan mempertanyakan bagaimana institusi agama memediasi hubungan antara manusia dan ketuhanan.
Dari segi akting, Aamir Khan sebagai PK memiliki karakteristik yang ekspresif, naif, dan komikal, yang dalam banyak hal mengingatkan pada Mr. Bean. Namun, lebih dari sekadar humor slapstick, PK adalah figur yang memadukan elemen dari Paul the Alien dalam Paul (2011), sarkasme Bill Maher dalam Religulous (2008), serta tradisi mistik sufi yang menempatkan Tuhan sebagai entitas yang harus dicari dengan kejujuran dan pertanyaan yang kritis. Humor dalam PK berfungsi sebagai alat untuk mengungkap paradoks dalam sistem keagamaan, sebagaimana dikemukakan oleh Mikhail Bakhtin dalam The Dialogic Imagination, di mana komedi dapat menjadi alat subversif terhadap wacana dominan yang hegemonik.
Dalam tradisi sufi, humor dan paradoks sering digunakan untuk mengajukan pertanyaan mendasar tentang Tuhan dan agama, seperti dalam kisah-kisah Nasruddin Hoja. Film ini menggunakan strategi yang sama: PK mempertanyakan ritual dan dogma keagamaan dengan kepolosan, bukan dengan kebencian. Namun, justru dalam kepolosan itulah muncul kritik tajam terhadap kemunafikan dan kontradiksi dalam agama yang terorganisir. Fenomena ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Emile Durkheim dalam The Elementary Forms of Religious Life, bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai alat untuk mengontrol masyarakat melalui norma dan regulasi sosial.
Di titik ini, PK menjadi kritik pedas terhadap otoritas agama, terutama dalam konteks bagaimana agama digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Kritik terhadap agama dalam film ini serupa dengan pandangan Richard Dawkins dalam The God Delusion, yang menyatakan bahwa agama bukan hanya sekadar keyakinan spiritual, tetapi juga struktur sosial yang mempertahankan hierarki dan memperalat ketakutan manusia untuk kepentingan institusional. Namun, perbedaan fundamental antara PK dan kritik Dawkins adalah pendekatan spiritualnya yang tetap mengakui kemungkinan eksistensi Tuhan, meski mempertanyakan cara manusia memperlakukannya sebagai komoditas. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Karen Armstrong dalam A History of God, yang menyoroti bagaimana agama sering kali mengalami pergeseran dari pengalaman mistik menuju institusi kekuasaan.
Dalam kajian sinema, film seperti PK dapat diposisikan sebagai bagian dari counter-narrative terhadap dominasi ideologi tertentu dalam masyarakat. Mikhail Bakhtin dalam The Dialogic Imagination menekankan bahwa komedi dan satir merupakan bentuk wacana yang menantang narasi tunggal (monologic discourse) yang sering digunakan oleh institusi kekuasaan untuk mempertahankan hegemoninya. Dalam hal ini, PK menawarkan narasi alternatif yang mempertanyakan otoritas agama tanpa sepenuhnya menyangkal nilai spiritualitas.
Jika melihat sejarah sinema India, PK bukanlah film pertama yang menyoroti persoalan agama. Sebelumnya ada Oh My God! (2012), yang mengangkat kritik serupa dengan pendekatan yang lebih ringan. Namun, PK lebih provokatif dan tajam dalam mengeksplorasi bagaimana agama dapat dijadikan alat manipulasi sosial. Ini sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci dalam Selections from the Prison Notebooks, bahwa agama kerap digunakan sebagai alat hegemoni budaya untuk membentuk dan mengendalikan kesadaran kolektif masyarakat.
Yang menarik, PK tidak menawarkan ateisme sebagai solusi atas persoalan agama. Sebaliknya, film ini mengajukan pertanyaan: apakah mungkin ada keberagamaan yang lebih otentik, yang tidak dimediasi oleh institusi dan hierarki? Pertanyaan ini tetap relevan dalam berbagai konteks, termasuk di Indonesia, bahwa agama sering kali lebih dimanfaatkan sebagai alat politik dibandingkan sebagai praktik spiritual yang murni.
PK adalah film yang mengajak kita untuk menertawakan hal-hal yang sering kita anggap sakral, bukan untuk meremehkannya, tetapi justru untuk memahami esensinya. Kritik dalam film ini tidak ditujukan untuk menghancurkan kepercayaan, tetapi justru untuk menantang manusia agar memahami keyakinan mereka dengan lebih jujur dan autentik. Tentu saja, PK bukan film untuk semua orang. Mereka yang terlalu nyaman dengan dogma mungkin akan merasa terganggu. Namun, bagi mereka yang percaya bahwa agama seharusnya lebih dekat dengan hati manusia ketimbang sekadar instrumen kekuasaan, PK adalah satir yang relevan dan menyegarkan.
Film-Film India Lain yang Patut Diperhitungkan
OMG: Oh My God! (2012)
Jika PK mengkritik agama melalui satir alien, OMG: Oh My God! melakukannya lewat jalur hukum. Kanji, seorang pedagang Hindu-ateis, menuntut Tuhan ke pengadilan setelah tokonya hancur akibat Act of God. Premis yang terdengar absurd ini menggugat bagaimana institusi agama sering kali memanfaatkan konsep ketuhanan untuk kepentingan ekonomi dan sosial. Kritik ini mengingatkan pada gagasan lawas Feuerbach yang menyatakan bahwa agama sering kali diciptakan untuk melayani kebutuhan manusia, bukan sebaliknya. Dalam konteks ini, OMG mengajukan pertanyaan fundamental tentang relasi antara agama, ekonomi, dan kekuasaan.of Wasseypur (2012)
Film ini adalah epik Mumbai Noir yang brutal, mengisahkan perebutan kekuasaan di kawasan ghetto bernama Wasseypur. Dibandingkan dengan narasi mafia ala Martin Scorsese, film ini menampilkan dunia bawah tanah yang lebih mentah, penuh dengan dendam yang diwariskan lintas generasi. Sutradara Anurag Kashyap menciptakan film yang tidak hanya bergaya dokumenter dalam estetika kekerasannya, tetapi juga mengajukan pertanyaan tentang lingkaran balas dendam dan bagaimana kekerasan dapat menjadi warisan budaya yang diturunkan tanpa henti.
Satya (1998)
Sebagai pionir Mumbai Noir, Satya mendobrak narasi klasik Bollywood dengan menampilkan realisme kejahatan jalanan yang gelap dan nihilistik. Film ini menggambarkan bagaimana cinta dan kebencian, ketika bertemu dalam realitas kota yang keras, dapat menghancurkan manusia. Jika Gangs of Wasseypur adalah mahakarya epik tentang gangster, maka Satya adalah elegi bagi mereka yang terjebak dalam pusaran kekerasan yang tak terhindarkan. Karya ini dapat dibaca dalam konteks teori subaltern yang dikembangkan oleh Gayatri Spivak, yang menjelaskan bagaimana masyarakat marginal sering kali tidak memiliki suara dalam struktur sosial yang lebih luas.
Omkara (2006)
Film ini adalah adaptasi Othello dalam konteks India, menghadirkan cerita yang lebih panas dan lebih intens. Vishal Bhardwaj, seperti dalam Haider, menunjukkan bagaimana Shakespeare dapat menemukan relevansi yang lebih tajam ketika diterjemahkan ke dalam dinamika politik dan kasta di India. Di tangan Bhardwaj, Othello tidak hanya tentang kecemburuan, tetapi juga politik identitas, kesetiaan, dan pengkhianatan yang berakar dalam lanskap sosial India
Raman Raghav 2.0 (2016)
Nawazuddin Siddiqui menampilkan salah satu peran terbaiknya sebagai pembunuh berantai psikopat yang menganggap dirinya mesias. Film ini bermain di wilayah yang sama dengan Taxi Driver (1976) dan Joker (2019), di mana kegilaan dan kekerasan bukan sekadar tindakan individu, tetapi juga refleksi dari masyarakat yang telah gagal memahami dirinya sendiri karena negara dan institusi sosial memiliki kontrol terhadap tubuh dan identitas individu, yang dalam kasus ini, terwujud dalam karakter Raman yang merepresentasikan produk dari masyarakat yang rusak.
Madras Café (2013)
Sebuah spy thriller yang terasa seperti Jason Bourne versi India, tetapi dengan kedalaman politik yang lebih kuat. Berbeda dari film aksi India kebanyakan, Madras Café lebih subtil dan membangun ketegangan dengan narasi yang kompleks, membongkar sejarah konflik Tamil yang jarang dibahas dalam arus utama perfilman India. Film ini dapat dianalisis dalam konteks geopolitik seperti yang dijelaskan oleh Benedict Anderson (1983) dalam Imagined Communities, yang menyoroti bagaimana narasi sejarah dan konflik etnis sering kali dikonstruksi dalam wacana nasionalisme.
Swades (2004)
Mungkin film terbaik Shah Rukh Khan. Berbeda dari citra megabintang Bollywood yang sering diasosiasikan dengannya, dalam film ini ia tampil lebih reflektif sebagai ilmuwan NASA yang kembali ke India dan menemukan makna baru dalam hidupnya. Swades adalah film tentang diaspora, identitas, dan pertanyaan besar tentang tanah air: apakah kita kembali ke akar karena kewajiban, atau karena ada sesuatu yang lebih besar yang memanggil kita pulang?
Sinema, Kritik, dan Perubahan
Dari Haider yang politis, PK yang satir, hingga Swades yang reflektif, Bollywood tidak selalu tentang tarian dan drama over-the-top. Ada film-film yang berbicara tentang manusia, kekuasaan, agama, dan sejarah dengan cara yang lebih dalam. Pertanyaannya, apakah di Indonesia ada ruang untuk film-film semacam ini? Jika melihat sejarah sinema nasional, sulit membayangkan sebuah film yang berani berbicara seterbuka Haider atau PK dapat bertahan. Sensor dan kontrol narasi negara sering kali menjadi hambatan bagi film-film yang mencoba menampilkan realitas sosial yang kritis.
Dua film dokumenter karya Joshua Oppenheimer, The Act of Killing (2012) dan The Look of Silence (2014), adalah contoh bagaimana film dengan muatan sosial-politik yang kuat dapat dicekal karena dianggap mengganggu narasi resmi. Konteks ini relevan dengan konsep state of exception yang dikembangkan oleh Giorgio Agamben (2005) dalam State of Exception, yang menjelaskan bagaimana negara sering kali menciptakan kondisi hukum yang fleksibel untuk membungkam wacana yang berpotensi mengganggu stabilitas kekuasaan.
Maka, bisa kita bayangkan, jika suatu hari ada film Indonesia yang menampilkan kritik setajam Haider, atau mempertanyakan agama seperti PK, kemungkinan besar ia akan langsung dicap sebagai penghancur moral bangsa. Sampai saat itu tiba, saya akan terus menonton dan menulis—karena, seperti ungkapan Alejandro Jodorowsky: “Movies are not just industry. They are the search for the human soul”. Dan mungkin, juga pencarian terhadap siapa kita sebenarnya.
Editor: Hafidz Azhar