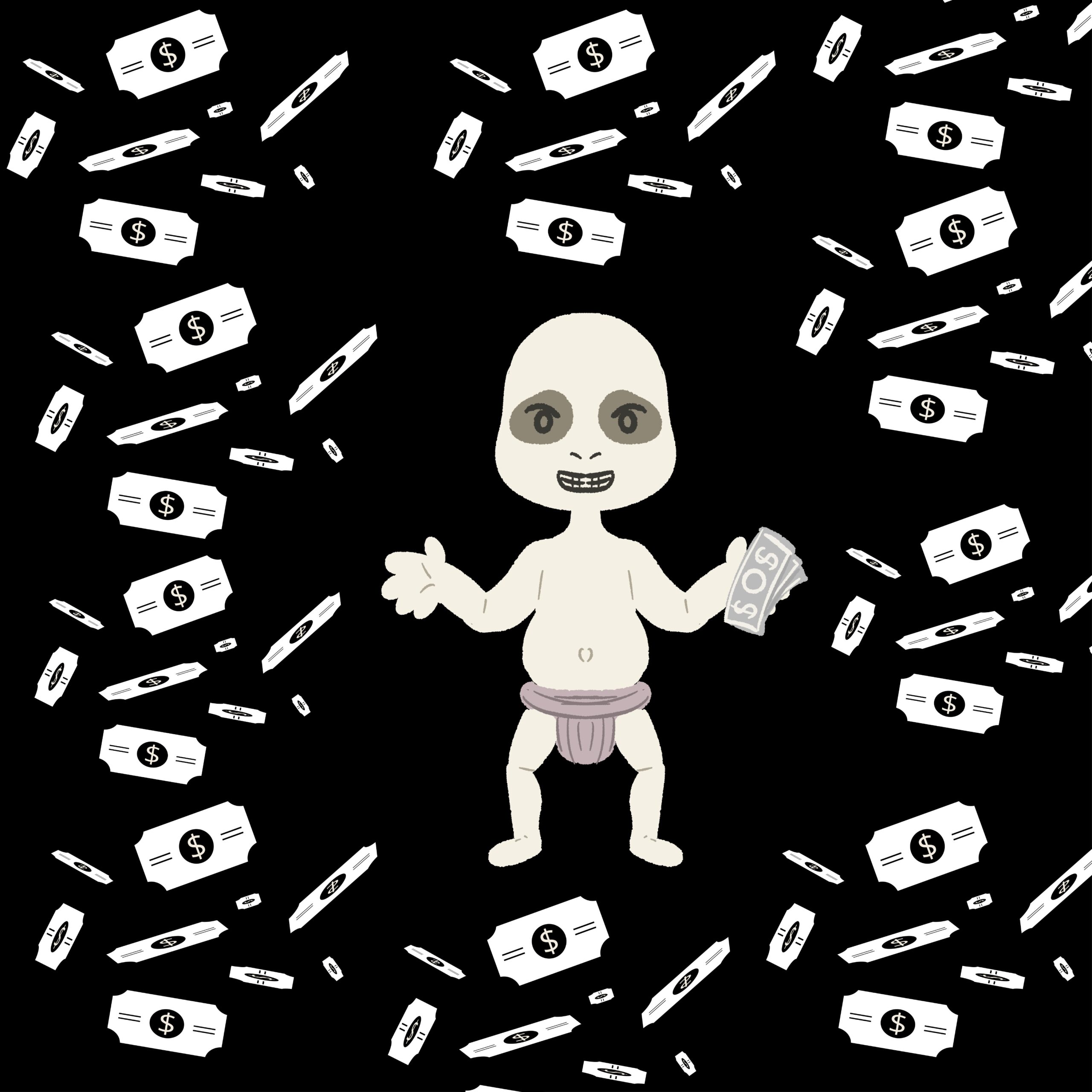Dalam enam bulan terakhir sering saya merasa kurang uang. Saya tidak lagi jadi pejabat universitas, tidak pula mendapat banyak pekerjaan sampingan seperti menyunting naskah buku atau menerjemahkan buku asing, lagi pula usaha penerbitan koran dan majalah yang begitu lama menambah pendapatan saya dari penulisan kolom reguler tidak lagi bagus. Dengan kata lain, saya hanya mengandalkan gaji dosen swasta ditambah tunjangan negara yang, tentu saja, tidak sebesar tunjangan buat para profesor.
Namun, saya tidak merasa miskin, meski juga tidak merasa kaya. Dalam periode itu saya tidak sampai menjual mobil tua atau menggadaikan motor yang sama tuanya, apalagi menjual tanah warisan. Jumlah telur ayam di dapur, sebagai indikator kesejahteraan rumah tangga kami, masih normal kecuali dalam satu-dua hari di penghujung bulan. Ngopi, udud, dan keluyuran tetap mengisi kebiasaan saya. Kekurangan uang hanya terasa ketika saya mau memesan buku atau mau membeli barang-barang yang tidak begitu perlu seperti baju atau sepatu. Selebihnya, hidup saya sangat bahagia: istri sehat, dua di antara ketiga anak kami sudah mandiri. Mau apa lagi, coba?
Seingat saya, tidak pernah saya berniat cari uang. Pendidikan dan gembelengan orang tua, juga teladan para senior di lingkungan sehari-hari saya, tidak mengarahkan saya ke jurusan itu. Saya hanya berikhtiar mengerjakan apa yang menurut pendirian saya patut saya kerjakan, katakanlah sebatas menjalankan darma saya di muka bumi. Setidaknya, itulah yang selalu saya katakan kepada diri sendiri. Misalnya, ketika hendak pergi ke kampus, saya berkata kepada diri sendiri, “Pagi ini aku mau mengajar untuk menjalani tugasku sebagai dosen.” Selebihnya, uang cenderung saya anggap barang gaib, yang akan datang sendiri, terutama kalau saya tidak mengkhianati apa yang telah menjadi darma saya. Kalaupun sesekali uang tidak datang di kala saya memerlukannya, saya anggap hal itu semata-mata soal dinamika waktu.
Contoh soal waktu itu terlihat dari dua pengalaman kecil saya. Sewaktu saya membantu sebuah perusahaan swasta di Bandung, pernah sekali saya tidak mendapatkan honorarium bulanan, tapi saya tidak mengajukan komplain apa-apa. Bulan berikutnya, barulah sang juru bayar mengoreksi kekeliruan administratifnya. Honor saya jadi dobel dong. Pernah juga ada pengalaman lucu dengan orang admin dari sebuah universitas di Australia. Karena saya sempat jadi peneliti tamu di situ, rupanya ada dana yang jadi hak saya, dan tentu saja orang admin mengurusnya dengan baik. Celakanya, saya baru menyadari hal itu lebih kurang setahun kemudian setelah saya berulang kali menerima surat elektronik dari pihak universitas. Atas bantuan sorang rekan di sana, selamatlah saya dari kecenderungan gaptek nan memalukan: cukup mengklik acceptance dalam transaksi digital. Oh, senangnya bukan kepalang, seakan-akan saya mendapat harta karun dari tanah seberang.
Kalau saya menganggap uang itu gaib — dalam arti buat apa kita mengejar-ngejar barang yang tidak terlihat –, lain orang lain pula anggapannya, tentu. Kalau saya tidak keliru sangka, mereka menggaibkan siasat cari uang: sembunyi-sembunyi, bergelap-gelap, ada main. Tidak sedikit orang Indonesia, terutama di Jawa, yang pernah menggandrungi tuyul, sampai-sampai di Klaten pada pertengahan dasawarsa 1980-an pernah digelar seminal tuyul segala. Bidang amatannya dikasih istilah tersendiri waktu itu, yakni “parapsikologi”. Maafin, ya, Yul, kalau saya salah sangka.
Samar-samar saya melihat uang sebagai tapak iblis dalam diri manusia. Jangan sampai tapak itu terlihat oleh orang banyak. Itu sebabnya uang disembunyikan dalam dompet, dikunci dalam brankas, dilindungi dalam bank, atau dicuci di pasar barang seni. Kalaupun sesekali orang sanggup memperlihatkan uang berhamburan dari tangannya, itu hanya bisa terjadi dalam keadaan setengah sadar atau setengah mabuk, misalnya sewaktu orang bergoyang-goyang di panggung dangdut atau ketika nama orang dipanggil-panggil oleh sinden di panggung kliningan.
Oleh sebagian orang beruang, sebagaimana yang lazim dilakukan terhadap iblis, uang itu disuruh bersujud di hadapan nilai-nilai luhur yang jadi dasar keyakinan. Timbullah filantrofi, sejenis titian sosial bagi orang-orang kaya untuk membangun harkatnya di lingkungan masyarakat luas. Dari kegiatan itu berdiri banyak hal yang bermanfaat bagi orang banyak, misalnya panti asuhan, panti jompo, observatorium, sekolah, dan rumah sakit. Namun, layaknya iblis, ada kalanya uang seakan ogah bersujud di hadapan cita-cita manusia. Itu terlihat dari perilaku sebagian orang beruang lainnya, terutama orang kaya baru yang pada dasarnya memendam dendam terhadap masa lalu. Mereka sepertinya gagal menemukan tonggak kebahagiaan selain pamer kekayaan. Timbullah beragam perilaku aneh yang belakangan disebut flexing, yang di hati orang banyak yang hidupnya susah tidak mustahil malah memantik amarah. Si kaya yang keranjingan flexing seperti kekurangan cadangan empati.
Di sela-sela kerusuhan Agustus, presiden Republik Indonesia dikabarkan mengundang para pembesar dari lingkungan dekatnya. Kata si empunya kabar, dalam pertemuan itu kepala negara dan pemerintahan meminta hadirin untuk berhenti main flexing dalam media sosial. Ketika saya mendengar berita itu, saya bertanya-tanya: apa lawan kata dari flexing? Berpura-pura miskin atau bagaimana? Saya tidak tahu. Yang jelas, Bapak Presiden diharapkan menjalankan kebijakan ekonomi yang tidak sebatas menyentuh gejala. Jangan pula masalah ekonomi dihadapi dengan main politik.
Ketika kerusuhan mereda di berbagai kota, saya kembali menggenjot sepeda dari Ledeng ke Lembang. Seperti biasa, saya beristirahat di dekat jejeran pedang makanan dan minuman di tepi jalan. Iseng-iseng saya buka aplikasi m-banking pada ponsel saya. Alhamdulillah, ternyata ada sedikit uang masuk ke dalam rekening saya dari penerbit surat kabar yang masih mau memuat kartun editorial mingguan buatan saya. “Nyuhunkeun sapuluh, nya, Bu. Dibungkus,” pinta saya kepada penjaja kue balok.
Sambil meluncur pulang, merasakan sejuknya angin pegunungan, saya merasa bahwa soal yang saya hadapi bukanlah kekurangan atau kelebihan uang, melainkan kesanggupan menyesuaikan diri dengan perjalanan waktu.***
Editor: Hafidz Azhar